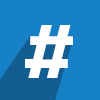Oleh: Khikmawanto, Direktur Eksekutif Renaissance Institute dan Pengajar di Universitas Yuppentek Indonesia
TANGERANGNEWS.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah mega-proyek gizi dengan niat yang sesungguhnya mulia, sebuah investasi vital pada generasi emas. Namun, realitas implementasi kini terasa pahit, di mana media dipenuhi berita keracunan, memaksa sorotan publik teralih dari visi besar ke dapur-dapur sekolah yang bermasalah. Analisis kita harus beranjak dari sekadar menyalahkan juru masak di tingkat sekolah menuju meja perencanaan anggaran dan pengadaan di tingkat pusat.
Masalah fundamental MBG terletak pada paradoks anggaran yang sangat politis: dorongan untuk melayani sebanyak mungkin anak dengan dana yang tersedia memaksa harga per porsi ditekan serendah mungkin, menciptakan Tiran Efisiensi di mana biaya yang dihemat di awal harus dibayar mahal dengan risiko kesehatan anak di kemudian hari. Ketika margin keuntungan tipis—suatu skenario yang lumrah terjadi dalam pengadaan masif—yang pertama dikorbankan adalah kualitas bahan baku dan standar kebersihan. Inilah titik kritisnya: kasus keracunan bukan kecelakaan acak, melainkan hasil logis dari tekanan sistemik yang menukarkan keamanan pangan demi cakupan yang luas dan cepat.
Lebih jauh dari masalah anggaran, ironi kebijakan ini terletak pada mekanisme tata kelolanya yang menerapkan Desentralisasi Semu. Secara formal, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan menjadi garda terdepan pengawasan dan eksekutor program di lapangan. Namun, kenyataannya, mereka seringkali hanya menjadi "juru antar" kegagalan. Keputusan krusial mengenai siapa mitra katering besar yang akan beroperasi, spesifikasi menu, dan berapa harga per porsi makanan, sebagian besar dikunci di tingkat pusat, seringkali melalui mekanisme pengadaan yang hanya bisa dijangkau oleh perusahaan skala nasional. Sementara kekuasaan dan kontrol kualitas tersentralisasi, beban operasional, pengawasan distribusi harian, dan yang terberat, tanggung jawab krisis saat terjadi keracunan, sepenuhnya didorong ke Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Dinas Kesehatan setempat. Pemda dipaksa menjalankan mandat tanpa diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi kontraktor yang paling kompeten atau memaksakan standar kualitas yang ketat.
Fenomena ini, dalam studi kebijakan publik, dikenal sebagai unfunded mandates atau pelimpahan tanggung jawab tanpa disertai sumber daya dan kontrol yang memadai, suatu kegagalan struktural dalam desain kebijakan. Ini menciptakan risiko moral di mana mitra katering besar tidak memiliki akuntabilitas langsung kepada komunitas yang mereka layani. Sebagaimana dijelaskan oleh Aaron Wildavsky dalam karyanya tentang studi anggaran, kebijakan cenderung gagal bukan karena visinya yang tidak tepat, tetapi karena ketidaksesuaian antara ambisi program yang besar dengan realitas kapasitas implementasi dan pengawasan di lapangan. Mengingat variasi geografis dan logistik di Indonesia, model sentralistik ini sudah pasti tidak fit for purpose. Ia justru menciptakan ketidaksetaraan kualitas—di mana sekolah di kota besar mungkin mendapatkan katering yang lebih baik, sementara daerah terpencil menerima layanan yang rentan terhadap kegagalan.
Untuk menyelamatkan MBG, kita harus berhenti mengkritisi output (jumlah porsi) dan beralih fokus pada outcome (keamanan dan status gizi). Solusi ada pada membalik piramida insentif melalui desentralisasi yang sejati. Pemerintah harus berani mengakui dan menginternalisasi biaya risiko keamanan pangan dalam anggaran, yang berarti menaikkan harga per porsi secara realistis untuk menutupi biaya sertifikasi higiene dan audit mendalam. Lebih penting lagi, dana harus didesentralisasi langsung—bisa melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang earmarked atau mekanisme dana transfer spesifik lainnya. Kewenangan penuh harus diberikan kepada gugus sekolah atau Pemda untuk memilih katering lokal atau bahkan memberdayakan koperasi ibu-ibu di lingkungan sekolah.
Langkah desentralisasi sejati ini adalah solusi multi-dimensi. Pertama, ia meningkatkan akuntabilitas lokal karena katering kecil lebih takut kehilangan reputasi di komunitasnya daripada kontraktor raksasa dari ibu kota. Kedua, ia secara signifikan mendorong ekonomi lokal karena dana program berputar di daerah, menghidupkan warung, petani, dan UKM. Ketiga, ia menjamin kualitas bahan baku segar yang adaptif terhadap ketersediaan daerah, misalnya ikan di pesisir atau sayuran pegunungan, daripada bergantung pada pasokan yang telah menempuh perjalanan jauh.
MBG adalah program yang terlalu penting untuk digagalkan oleh tata kelola yang setengah-setengah. Kasus keracunan adalah alarm darurat yang memaksa kita berhenti dari ilusi cakupan massal. Inilah pertaruhan politik sebenarnya: jika sistem ini tidak segera direformasi dengan mengembalikan kedaulatan kualitas kepada daerah, program ini bukan hanya terancam gagal mencapai target gizi, tetapi yang lebih berbahaya, ia akan mengikis habis kepercayaan publik. Sebuah program yang tujuannya menyelamatkan generasi justru menjadi liabilitas politik jangka panjang. Jangan biarkan ambisi menumbuhkan generasi emas malah diakhiri dengan jejak kegagalan karena keengganan untuk mendesentralisasi kendali atas sepiring nasi.