Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya
Kamis, 15 Januari 2026 | 11:36
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.

Oleh: Alpun Hasanah, Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang
TANGERANGNEWS.com-"Semua sama di depan hukum" – klaim ini sering digaungkan sebagai prinsip dasar negara hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum justru kerap berwajah dua: tegas terhadap rakyat kecil, tetapi lentur bahkan tunduk pada penguasa dan elite politik.
Kasus-kasus korupsi yang dibiarkan, proses hukum yang mandek untuk pejabat, serta vonis ringan bagi pelaku kejahatan berdasi menunjukkan bahwa hukum bisa menjadi alat kekuasaan, bukan keadilan. Pertanyaannya: mengapa elite politik seolah kebal hukum? Dan apa dampaknya bagi demokrasi?
Hukum untuk Siapa? Sebuah Pertanyaan Dasar, Apakah Hukum untuk Rakyat atau Penguasa? Ketika Elite Politik Kebal Hukum
Di negeri yang katanya menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum, ironi terbesar justru terlihat jelas dalam relasi antara hukum dan kekuasaan. Contohnya ketika rakyat kecil bisa dihukum karena mencuri sepotong roti, vonis berat kepada pencuri ayam yang lapar, dibandingkan dengan politisi yang terlibat kasus korupsi berjilid-jilid namun hanya mendapatkan hukuman ringan—bahkan sering kali bebas sebelum masa hukuman berakhir karena "kelakuan baik” dengan tersenyum bebas di layar televisi, kita dipaksa bertanya: hukum ini untuk siapa sebenarnya? Untuk keadilan rakyat atau untuk melindungi para penguasa?
Hukum yang seharusnya hadir sebagai pelindung semua warga negara tanpa kecuali. Namun realitasnya, masyarakat sering menyaksikan bahwa hukum justru tampak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pertanyaan "Hukum untuk siapa?" bukan hanya retorik, tetapi menjadi refleksi sosial tentang bagaimana hukum dijalankan.
Di negara demokratis, idealnya hukum menjadi panglima tertinggi. Namun dalam praktik, banyak elite politik atau pejabat tinggi yang justru tampak "kebal" dari jerat hukum, meski ada dugaan kuat keterlibatan mereka dalam berbagai kasus. Ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.
Jika hukum tidak lagi dipercaya sebagai sarana keadilan, maka masyarakat akan cenderung mencari keadilan di luar sistem. Hal ini berbahaya, karena membuka ruang untuk anarkisme, vigilantisme, atau bahkan apatisme sosial. Ketidakpercayaan terhadap hukum sama artinya dengan ketidakpercayaan terhadap negara itu sendiri.
Budaya Impunitas (Budaya Kekebalan Hukum): Ketika Kekuasaan Menyandera Keadilan
Yang lebih membahayakan bukan sekadar ketidakadilan itu sendiri, tetapi normalisasi terhadap ketidakadilan. Kita, sebagai masyarakat, mulai terbiasa melihat pejabat korup tertawa saat sidang, atau tokoh politik yang masih bisa mencalonkan diri meski pernah terlibat skandal hukum. Inilah yang disebut budaya impunitas—keadaan ketika seseorang bisa melanggar hukum tanpa takut akan dihukum.
Para elite kerap memanfaatkan posisi, jaringan, dan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi proses hukum. Intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum, penggunaan aparat untuk tujuan politis, hingga penghapusan kasus lewat jalur non-yuridis menjadi fenomena yang kian membahayakan supremasi hukum.
Budaya impunitas adalah kanker dalam sistem demokrasi. Ia melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, mematikan semangat pemberantasan korupsi, dan mengikis semangat moral dalam kehidupan berbangsa. Ketika rakyat menyaksikan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah, maka tidak ada lagi kepercayaan pada sistem—yang tersisa hanyalah frustrasi, sinisme, dan kemarahan yang diam-diam.
Yang lebih menyedihkan adalah ketika publik mulai “terbiasa” dengan ketidakadilan ini. Media memberitakan, masyarakat marah, tapi kemudian melupakan. Elite pun belajar satu hal penting: selama mereka bisa mengontrol narasi dan institusi, hukum tidak akan menyentuh mereka.
Ketimpangan Hukum: Rakyat Kecil sebagai Korban Abadi
Dalam ketimpangan ini, rakyat kecil menjadi korban utama, sementara elite bisa lolos dari hukum,. Mereka tidak punya kuasa untuk membela diri, tidak punya akses ke pengacara hebat, dan bahkan tidak tahu bagaimana caranya menghadapi sistem hukum yang kompleks dan elitis. Bagi mereka, hukum adalah alat represi, bukan perlindungan. Kasus pencurian kecil-kecilan demi bertahan hidup bisa dijatuhi hukuman berat, sementara korupsi miliaran rupiah justru diselesaikan dengan vonis ringan atau bahkan pemutihan.
Pengadilan seharusnya menjadi tempat terakhir rakyat menggantungkan harapan. Namun ketika keadilan hanya bisa diakses oleh mereka yang punya kuasa dan uang, maka keadilan kehilangan makna substantifnya. Rakyat tidak hanya mengalami ketidakadilan hukum, tetapi juga ketidakadilan sosial yang berlapis.
Contoh nyata dari ketimpangan ini bisa dilihat dalam kasus-kasus kriminalisasi petani, nelayan, aktivis lingkungan, atau buruh yang memperjuangkan haknya kerap muncul dalam pemberitaan. Mereka dijerat dengan pasal-pasal yang kabur, ditangkap tanpa proses yang transparan, dan disidangkan tanpa pembelaan yang memadai. Ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral: negara telah abai terhadap mereka yang seharusnya paling dilindungi.
Mengembalikan Marwah Hukum: Antara Harapan dan Realitas
Pertanyaannya kini: mungkinkah hukum kembali menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan? Jawabannya tergantung pada keberanian institusi hukum dan tekanan publik yang konsisten. Reformasi hukum tidak akan terjadi tanpa kemauan politik, dan kemauan itu tidak akan muncul tanpa desakan masyarakat. Hukum hanya bisa kembali berfungsi sebagai alat keadilan jika masyarakat terus menekan, jika media tidak bungkam, dan jika lembaga-lembaga hukum benar-benar independen dari intervensi politik.
Reformasi hukum tidak bisa setengah hati. Kita butuh jaksa dan hakim yang tidak takut pada tekanan politik, aparat kepolisian yang bersih dari korupsi, serta lembaga antikorupsi yang benar-benar independen. Lebih dari itu, kita butuh kesadaran kolektif bahwa keadilan adalah fondasi dari negara—bukan sekadar jargon dalam pidato politik. Tidak cukup hanya membentuk lembaga baru, tetapi juga memperbaiki budaya hukum yang selama ini permisif terhadap pelanggaran oleh elite.
Namun di tengah pesimisme, masih ada harapan. Lembaga seperti KPK (meski kini kian dilemahkan), pers investigatif, LSM hukum, dan masyarakat sipil tetap menjadi garda terakhir dalam menjaga marwah hukum. Tapi untuk itu, rakyat harus tetap bersuara—karena diam adalah bentuk dukungan terhadap ketidakadilan.
Saatnya Hukum Tidak Lagi Tunduk pada Kekuasaan, Jangan Diam Melihat Ketidakadilan
Keadilan yang berat sebelah tidak hanya melukai rasa keadilan rakyat, tetapi juga melemahkan legitimasi negara. Negara yang adil adalah negara yang berani menegakkan hukum bahkan kepada pemegang kekuasaan tertinggi sekalipun. Saat hukum hanya menjadi alat kekuasaan, maka negara kehilangan wajah kemanusiaannya. Sebab negara bukan sekadar institusi, tetapi kontrak moral antara rakyat dan pemerintah. Dan dalam kontrak itu, hukum seharusnya menjadi jaminan keadilan, bukan pelindung para penguasa.
Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menundukkan rakyat, apalagi menjadi tameng bagi para penguasa. Saatnya hukum kembali ke hakikatnya: sebagai penjaga keadilan, bukan pelayan kekuasaan. Jika tidak, kita hanya hidup dalam negara hukum secara formal, namun tanpa keadilan sejati.
Diam adalah bentuk penerimaan terhadap ketidakadilan. Maka saatnya masyarakat bersuara, menolak tunduk pada sistem hukum yang timpang. Hukum harus kembali menjadi milik rakyat—bukan milik penguasa.
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.
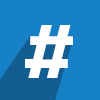 TODAY TAG
TODAY TAGSat Lantas Polres Metro Tangerang Kota menerapkan rekayasa lalu lintas selama beberapa hari ke depan seiring dengan penggunaan lokasi tersebut sebagai salah satu titik syuting film internasional terbaru yang dibintangi Lisa BLACKPINK

Persita Tangerang langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya setelah bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.
 RECOMENDED
RECOMENDED Tangerang News
Tangerang News @tangerangnews
@tangerangnews